Sebuah kesenian rakyat Gayo yang dikenal dengan nama Didong, yaitu suatu kesenian yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Didong dimulai sejak zaman Reje Linge XIII. Kesenian ini diperkenalkan pertama kali oleh Abdul Kadir To`et. Kesenian didong lebih digemari oleh masyarakat Takengon dan Bener Meriah.
Ada yang berpendapat bahwa kata “didong” mendekati pengertian kata
“denang” atau “donang” yang artinya “nyanyian sambil bekerja atau untuk
menghibur hati atau bersama-sama dengan bunyi-bunyian”. Dan, ada pula
yang berpendapat bahwa Didong berasal dari kata “din” dan “dong”. “Din”
berarti Agama dan “dong” berarti Dakwah.
Pada awalnya didong digunakan sebagai sarana bagi penyebaran agama Islam melalui media syair.
Para ceh didong (seniman didong) tidak semata-mata menyampaikan tutur
kepada penonton yang dibalut dengan nilai-nilai estetika, melainkan di
dalamnya bertujuan agar masyarakat pendengarnya dapat memaknai hidup
sesuai dengan realitas akan kehidupan para Nabi dan tokoh yang sesuai
dengan Islam. Dalam didong ada nilai-nilai religius, nilai-nilai
keindahan, nilai-nilai kebersamaan dan lain sebagainya. Jadi, dalam
ber-didong para ceh tidak hanya dituntut untuk mampu mengenal
cerita-cerita religius tetapi juga bersyair, memiliki suara yang merdu
serta berperilaku baik. Pendek kata, seorang ceh adalah seorang seniman
sejati yang memiliki kelebihan di segala aspek yang berkaitan dengan
fungsinya untuk menyebarkan ajaran Islam. Didong waktu itu selalu
dipentaskan pada hari-hari besar Agama Islam.
Dalam perkembangannya, didong tidak hanya ditampilkan pada hari-hari besar agama Islam, melainkan juga dalam upacara-upacara adat
seperti perkawinan, khitanan, mendirikan rumah, panen raya, penyambutan
tamu dan sebagainya. Para pe-didong dalam mementaskannya biasanya
memilih tema yang sesuai dengan upacara yang diselenggarakan. Pada
upacara perkawinan misalnya, akan disampaikan teka-teki yang berkisar
pada aturan adat perkawinan. Dengan demikian, seorang pe-didong harus
menguasai secara mendalam tentang seluk beluk adat perkawinan. Dengan
cara demikian pengetahuan masyarakat tentang adat dapat terus
terpelihara. Nilai-nilai yang hampir punah akan dicari kembali oleh para
ceh untuk keperluan kesenian didong.
Penampilan didong mengalami perubahan setelah Jepang masuk ke Indonesia. Sikap pemerintah Jepang
yang keras telah “memporak-porandakan” bentuk kesenian ini. Pada masa
itu, didong digunakan sebagai sarana hiburan bagi tentara Jepang yang
menduduki tanah Gayo.
Hal ini memberikan inspirasi bagi masyarakat Gayo untuk mengembangkan
didong yang syairnya tidak hanya terpaku kepada hal-hal religius dan
adat-istiadat, tetapi juga permasalahan sosial yang bernada protes
terhadap kekuasaan penjajah Jepang. Pada masa setelah proklamasi, seni
pertunjukan didong dijadikan sebagai sarana bagi pemerintah dalam
menjembatani informasi hingga ke desa-desa khususnya dalam menjelaskan
tentang Pancasila, UUD 1945 dan semangat bela negara.
Selain itu, didong juga digunakan untuk mengembangkan semangat
kegotong-royongan, khususnya untuk mencari dana guna membangun gedung sekolah, madrasah, mesjid, bahkan juga pembangunan jembatan. Namun, pada periode 1950-an ketika terjadi pergolakan DI/TII kesenian didong terhenti karena dilarang oleh DI/TII.
Akibat dilarangnya didong, maka muncul suatu kesenian baru yang disebut
saer, yang bentuknya hampir mirip dengan didong. Perbedaan didong denga
saer hanya dalam bentuk unsur gerak dan tari. Tepukan tangan yang
merupakan unsur penting dalam didong tidak dibenarkan dalam saer.
Dewasa ini didong muncul kembali dengan lirik-lirik yang hampir sama ketika zaman Jepang, yaitu berupa protes (anti kekerasan). Bedanya, dewasa ini protesnya ditujukan kepada pemerintah yang selama sekian tahun menerapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer,
sehingga menyengsarakan rakyat. Protes anti kekerasan sebenarnya bukan
hanya terjadi pada kesenian didong, melainkan juga pada bentuk-bentuk kesenian lain yang ada di Aceh.
Satu kelompok kesenian didong biasanya terdiri dari para “ceh” dan
anggota lainnya yang disebut dengan “penunung”. Jumlahnya dapat mencapai
30 orang, yang terdiri atas 4–5 orang ceh dan sisanya adalah penunung.
Ceh adalah orang yang dituntut memiliki bakat yang komplit dan mempunyai
kreativitas yang tinggi. Ia harus mampu menciptakan puisi-puisi dan
mampu menyanyi. Penguasaan terhadap lagu-lagu juga diperlukan karena
satu lagu belum tentu cocok dengan karya sastra yang berbeda. Anggota
kelompok didong ini umumnya adalah laki-laki dewasa. Namun, dewasa ini
ada juga yang anggotanya perempuan-perempuan dewasa. Selain itu, ada
juga kelompok remaja. Malahan, ada juga kelompok didong remaja yang
campur (laki-laki dan perempuan). Dalam kelompok campuran ini biasanya
perempuan hanya terbatas sebagai seorang Céh.
Peralatan yang dipergunakan pada mulanya bantal (tepukan bantal) dan
tangan (tepukan tangan dari para pemainnya). Namun, dalam perkembangan
selanjutnya ada juga yang menggunakan seruling, harmonika, dan alat
musik lainnya yang disisipi dengan gerak pengiring yang relatif
sederhana, yaitu menggerakkan badan ke depan atau ke samping.
Pementasan didong ditandai dengan penampilan dua kelompok (Didong Jalu)
pada suatu arena pertandingan. Biasanya dipentaskan di tempat terbuka
yang kadang-kadang dilengkapi dengan tenda. Semalam suntuk kelompok yang
bertanding akan saling mendendangkan teka-teki dan menjawabnya secara
bergiliran. Dalam hal ini para senimannya akan saling membalas
“serangan” berupa lirik yang dilontarkan olah lawannya. Lirik-lirik yang
disampaikan biasanya bertema tentang pendidikan, keluarga berencana,
pesan pemerintah (pada zaman Orba), keindahan alam maupun kritik-kritik
mengenai kelemahan, kepincangan yang terjadi dalam masyarakat. Benar
atau tidaknya jawaban akan dinilai oleh tim juri yang ada, yang biasanya
terdiri dari anggota masyarakat yang memahami ddidong ini secara
mendalam.




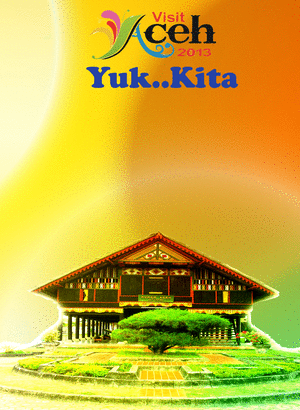












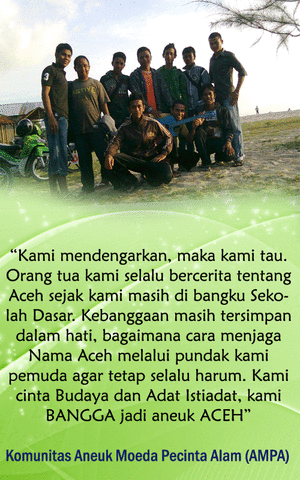














0 comments:
Post a Comment